[no_Sidebar]
 |
| Hyundai Kona Electric (Sumber: Hyundai Internusa) |
Pemerintah bilang kendaraan listrik merupakan salah satu upaya
mengurangi emisi karbon. Namun, semakin banyak
kendaraan listrik yang
diproduksi, semakin besar pula kebutuhan terhadap nikel, sehingga
pertambangan nikel akan semakin agresif. Akibatnya, ruang hidup hutan
semakin sempit sehingga emisi karbon tetap meningkat akibat deforestasi.
Selain itu, peran dan hak Masyarakat Adat di sekitar area tambang juga semakin dikerdilkan. Hal ini menimbulkan
paradoks, sehingga solusi nyata perlu segera dihasilkan.
― 10/04/2023
Percakapan sore hari kala itu agak lain. Biasanya kami disuguhi percakapan
trivia, tapi kali ini orang-orang bicara teknologi, sebuah topik yang
menggugah pikiran dan visioner. Sore itu saya putuskan untuk menjadi
penyimak, tidak mendebat, sekadar mengkritisi dalam hati sembari
mengobservasi.
Fenomena Kendaraan Listrik
Kendaraan listrik sudah banyak mengaspal di jalanan ibu kota. 9 dari 10
teman saya sudah pernah menumpangi sepeda motor listrik. 2 dari 10 sudah
mencoba mengendarainya sendiri. Dan 1 diantaranya sedang berencana untuk
memiliki kendaraan listrik sendiri.
Beberapa pengemudi dari perusahaan ojek online kini juga terlihat sudah
beroperasi dengan kendaraan listrik di jalanan ibu kota.
Elektrifikasi kendaraan memang sedang digalakan oleh pemerintah. Wajar
saja sih mengingat kini emisi karbon sudah mencapai angka yang
mengkhawatirkan. Sehingga untuk meminimalisirnya, kendaraan harus beralih
menggunakan sumber tenaga yang lebih ramah lingkungan.
Pembicaraan sore itu fokus kepada fenomena kendaraan lisrik yang kian
masif. Mulai dari suara kendaraannya yang lebih halus daripada sepeda; Perilisan Hyundai Kona yang disebut-sebut sebagai tanda menurunnya 'marwah' mobil listrik; Tutorial charging kendaraan listrik; Subsidi kendaraan listrik;
Biaya yang dihemat jika kita menggunakan kendaraan listrik, dan lain-lain.
Dari sekian banyak bahasan teknis, tidak terbesit sama sekali topik
tentang dampak negatif kendaraan listrik dalam aspek lingkungan dan
bagaimana kondisi ekologi negeri ini jika kendaraan listrik mendominasi
jalanan di masa mendatang.
Saat itu saya putuskan untuk meruntuhkan dinding dan turut memberikan
opini. Komponen utama dari kendaraan listrik itu
sendiri adalah Baterai, di mana untuk memproduksi baterai kendaraan listrik membutuhkan sumber daya tambang yang
menghasilkan nikel, litium, dan kobalt.
Otomatis, ruang hidup hutan akan semakin terkikis dengan bertambahnya
area tambang untuk produksi baterai. Belum lagi wacana Ibu Kota Baru
yang turut akan mempersempit area hutan. Kecemasan saya terpicu dengan
pikiran-pikiran tersebut. Saya mengutarakan kecemasan dan kegelisahan
saya akan hal ini dengan pendekatan yang halus dan bahasa yang tidak
menggurui.
Namun sayang, efek greenwashing ternyata sangat real.
Mentang-mentang dilabeli kata 'ramah lingkungan', orang-orang 'merasa'
bahwa suatu produk dengan label 'ramah lingkungan' lantas tidak
memiliki atau minim akan dampak negatif lingkungan. Padahal dalam
praktiknya, transisi kendaraan listrik dapat menambah intensitas
kerusakan lingkungan.
Saya menyaksikan sendiri betapa minimnya kepedulian orang sekitar saya
terhadap isu lingkungan. Bukannya mereka tidak mengerti, tetapi
sangat denial dan cenderung acuh.
"Ah, ga separah itu pencemaran lingkungan, nanti pemerintah yg mikirin
solusi"
"Oh, kasihan sih masyarakat pedalaman yang tertindas mafia tambang.
Tapi pasti nanti ada komunitas yang bantu kok. No worries!"
"Oke bumi ini butuh bantuan, tapi yasudah kan sudah ada pihak yang
memikirkan solusinya, kita ngapain repot."
"Kalau orang lain bisa bantu, kenapa harus gue? Gue mah bukan apa2,
kalau gue boros emisi karbon gabakal ngaruh sma orang2 kok"
Pemikiran-pemikiran tersebut menciptakan ilusi bahwa akan selalu ada
'pahlawan' yang akan menyelamatkan kita. Padahal seharusnya segala
perubahan itu dimulai dari yang kecil. Negara bisa berubah dimulai dari
perubahan satu komunitas. Satu komunitas mampu berubah dimulai dari satu
anggotanya. Segalanya dimulai dari diri kita sendiri.
Memang miris, tetapi tidak boleh membuat kita pesimis.
Inilah yang menjadi PR bagi kita para content creator:
Menemukan cara supaya orang-orang sekitar tergerak untuk turut
menjadi agen perubahan. Sekaligus melakukan pendekatan yang cukup
persuasif agar membuat orang sekitar tidak 'menggampangi' isu-isu
lingkungan.
Berapa Emisi Karbon yang Sebenarnya Bisa Dikurangi jika Kita Beralih Menggunakan
Kendaraan Listrik?
Satu hal yang pasti adalah: Orang-orang cenderung menyukai contoh nyata
dibandingkan membaca teori. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan
gambaran nyata mengenai efisiensi konsumsi daya satu mobil listrik.
Kita ambil satu contoh mobil listrik yaitu Hyundai Kona Electric. Daya
listrik yang diperlukan untuk men-charging penuh mobil ini adalah sebesar 2.640 watt, itu pun harus dilakukan selama 11 jam. Maka, rumah yang mampu melakukan charging 1 mobil listrik tersebut adalah rumah dengan kapasitas listrik di atas 2.200 watt.
Sementara, rata-rata kapasitas listrik rumahan di Indonesia adalah
1.300 watt - 2.200 watt. Opsi lain yang bisa dilakukan adalah charging kendaraan di SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Tetapi jumlahnya masih relatif kecil dan jarang ditemui. Selain itu, waktu charging juga cukup lama dan berisiko menyebabkan antrean panjang.
Bagaimana untuk motor listrik?
Daya listrik yang diperlukan untuk charging motor listrik adalah 450
watt, memang jauh lebih kecil dibandingkan mobil listrik.
Namun,
sumber listrik yang kita gunakan untuk men-charging kendaraan,
saat ini masih bergantung pada PLTU yang menggunakan bahan bakar
fosil. Jadi, meski emisi karbon yang kita hasilkan dari kendaraan berkurang,
tetapi emisi karbon yang kita hasilkan untuk charging kendaraan
tersebut jadi bertambah.
Contoh kasus: Penggunaan listrik di rumah Budi menghasilkan emisi karbon sebesar 4,6 ton/tahun.
Kendaraan Budi menghasilkan emisi karbon sebesar 3 ton/ tahun.
Maka, total emisi karbon yang dihasilkan oleh Budi setiap tahunnya = 4,6 + 3 = 7,6 ton/ tahun
Kemudian Budi memutuskan beralih ke kendaraan listrik dan hanya menghasilkan emisi karbon dari kendaraannya sebesar 0 ton/ tahun.
Namun karena harus men-charging motor listriknya setiap hari, emisi karbon dari penggunaan listrik rumahnya bertambah menjadi 6 ton/ tahun.
Jadi, total emisi karbon yang Budi hasilkan setiap tahunnya berkurang dari 4,6+3=7,6 ton/tahun menjadi 6ton/tahun saja (selisih 1,6 ton/ tahun).
*Angka diambil berdasarkan rata-rata emisi karbon per tahun yang dihasilkan per individu
Tentu
kasus di atas akan berbeda jika Budi sudah beralih menggunakan sumber
daya listrik terbarukan
seperti panel surya. Emisi karbon yang dihasilkan Budi tiap tahunnya bisa
hampir nol. Sayangnya di Indonesia, sumber daya listrik terbarukan masih
kurang digalakan.
Seharusnya, sumber daya listrik terbarukan harus digalakan terlebih
dahulu, baru lah kita berfokus pada elektrifikasi kendaraan.
Meskipun emisi karbon bisa berkurang dengan penggunaan kendaraan listrik,
tetapi selisihnya tidak sebanding dengan emisi karbon yang dihasilkan
dari deforestasi (penggundulan hutan) untuk memperluas area tambang demi
memproduksi baterai kendaraan listrik tersebut. Menurut studi yang dilakukan oleh Global Forest Watch,
setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 1 juta hektar hutan, yang
menyebabkan emisi sekitar 600 juta ton karbon dioksida.
Mengenal Suku Tobelo: Benteng Terakhir Hutan Halmahera

|
|
Anggota Masyarakat Adat Tobelo di hutan Halmahera. (Sumber: Faris
Bobero/ Mongabay Indonesia)
|
Suku Tobelo sudah eksis sejak abad 17. Bukti keberadaan mereka sudah
terlacak sejak era kesultanan Ternate hingga sekarang. Hutan Halmahera
adalah rumah bagi mereka selama lebih dari 3 abad.
Kemudian waktu terus berjalan seiring dengan peningkatan populasi. Semakin
tinggi populasi, artinya semakin banyak pula pemukiman yang
dibutuhkan.
Tahun 1960-an, upaya penyingkiran Masyarakat Adat Tobelo dimulai. Program
pemukiman mulai dilaksanakan besar-besaran dan sistematis oleh pemerintah
Indonesia. Deforestasi begitu masif sehingga ruang
hidup Masyarakat Adat Tobelo semakin menyempit.
Hal ini diperparah dengan stereotip tentang kelompok masyarakat
tradisional sebagai suku-suku terasing, terbelakang, primitif, dan
animis.
Tahun 1970-an, pemerintah Indonesia berusaha merelokasi Masyarakat Adat Tobelo. Meski imbauan pemerintah tersebut
dihargai oleh mereka, tetapi para tetua adat menolak.
Siapa yang nanti menjaga sumber air dan hutan? Mereka
bersikukuh untuk mempertahankan tradisi dan budaya.
Seumur hidup, mereka melihat hamparan hijau dari berbagai macam vegetasi,
buih putih sungai yang jernih, serta langit biru yang terbentang tanpa
terlihat pucuk bangunan. Kemudian, ada yang menyuruh mereka pindah ke
pemukiman sistemik dan berdekatan dengan masyarakat modern. Apakah mereka
akan terima begitu saja?
Dan ironisnya, sumber air dan pangan untuk masyarakat modern di pemukiman
modern itu sebagian besar berasal dari hutan yang dijaga
oleh Masyarakat Adat selama ratusan tahun lamanya. Sekarang para
penjaga sumber penghidupan itu malah di-anaktiri-kan. Bak air susu dibalas
air tuba.
Tidak cukup sampai di situ saja, pemerintah juga
mencederai kepercayaan dan budaya Masyarakat Adat Tobelo dengan
mengizinkan suatu perusahaan air kemasan beroperasi di Kali Molulu. Padahal, selain sebagai
sumber air, Masyarakat Adat Tobelo memiliki ikatan spiritual dengan Kali Molulu. Padi tumbuh subur dari
bawah kali tersebut. Air siap minum tersedia melimpah tanpa harus dimasak
terlebih dahulu.
Sebenarnya semua tindakan pemerintah adalah untuk kepentingan komunal dan
demi kesejahteraan bersama. Namun sayangnya Masyarakat Adat tidak terlalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Bahkan dalam beberapa kasus, perjanjian yang dibuat antara Masyarakat Adat dan pemerintah diingkari. Kepercayaan mereka sering kali
diciderai.
Tidak ada yang superior dan inferior antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Modern. Keduanya tidak bisa berkompetisi dan seharusnya
saling berkolaborasi. Masyarakat Adat seharusnya diberikan kebebasan melaksanakan tradisi
sembari menjaga alam. Masyarakat Modern dapat berperan dalam pemberian
modal dan edukasi mengenai teknik pengelolaan alam yang lebih maju dan
efisien.
Kriminalisasi Masyarakat
Adat Tobelo Pasca Ekspansi Tambang Nikel

|
|
Aksi Masyarakat Tobelo dalam menolak pertambangan nikel. (Sumber: Christ
Belseran/ Mongabay Indonesia)
|
Pernah nonton film korea Miracle in Cell No. 7? Film itu mengisahkan
seorang ayah tunggal yang mengidap autisme dan memiliki seorang anak kecil
perempuan. Sang ayah dipaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah
diperbuatnya. Dia harus divonis mati akibat tuduhan pembunuhan seorang anak
kecil.
Meskipun cerita film tersebut fiksi, ironisnya fenomena tersebut
benar-benar terjadi di dunia nyata. Hal tersebut terjadi lebih sering dan
lebih sadis dari yang kita duga, korbannya adalah warga yang tidak memiliki
kekuatan untuk melawan.
Pada 22 Maret 2023, pihak kepolisian di Halmahera Timur menangkap dan
menahan seorang Masyarakat Adat bernama Alen Baikole dari Suku Togutil,
Tobelo Dalam. Alen diduga telah mengalami penyiksaan saat penangkapan dan
interogasi oleh pihak kepolisian di Halmahera Timur. Alen Baikole
ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pelaku pembunuhan yang diduga
terjadi pada 29 Oktober 2022 di Kebun Semilo.
Padahal Alen memiliki alibi jelas yaitu, di waktu pembunuhan, Alen sedang
bersama istrinya. Selain itu, warga yang dibunuh pun berasal dari desa yang
jauhnya ratusan kilo meter dari desa Alen. Penyidik Polres Halmahera Timur
megintimidasi dan memaksa istri Alen yang berinisial Y untuk mengakui bahwa
Alen benar telah melakukan pembunuhan. Akibatnya, istri dan putri kecil Alen
mengalami trauma akan hal ini.
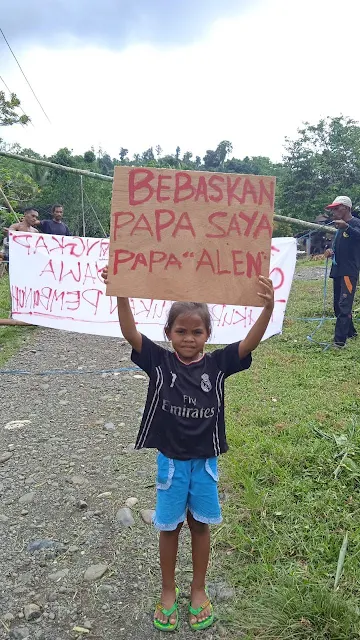
|
|
Putri dari Alen Baikole yang melakukan protes atas penangkapan
ayahnya. (Sumber: Aman.or.id)
|
Kasus kriminalisasi yang dilakukan polisi terhadap Masyarakat Adat Tobelo
Dalam, bukan lah yang pertama. Dilansir dari Mongabay, Syamsul Alam, Ketua PPMAN, mengatakan bahwa Alen Baikole, yang ditahan di
Polres Halmahera Timur diketahui
memiliki fakta-fakta atas dugaan “peradilan sesat” terhadap enam orang
Masyarakat Adat Tobelo Dalam, pada kasus tudingan pembunuhan
sebelum itu.
Hal ini membuat Masyarakat Adat Tobelo was-was karena
tudingan sebagai pembunuh berulang kali ditujukan pada mereka. Penangkapan Alen memberi ruang bagi kepolisian untuk menutupi skenario
kriminalisasi yang
membungkam kritik Masyarakat Adat Tobelo Dalam atas pembangunan yang
merusak lingkungan dan menghancurkan wilayah adat mereka. Diketahui bahwa PT. IWIP sudah meminta izin lahan yang cukup luas, tetapi akhir-akhir ini mereka meminta perluasan tambahan lagi kepada pemerintah.
Dampak Lingkungan dari Ekspansi Tambang Nikel di Halmahera
 |
| Aktivitas pertambangan yang terhenti setelah demo aksi Masyarakat Adat Tobelo. (Sumber: Christ Belseran/ Mongabay Indonesia) |
Selain dampak sosial budaya seperti yang dijabarkan di atas, ekspansi tambang nikel di Halmahera juga memberikan dampak lingkungan yang signifikan. Di tengah ambang krisis emisi karbon, Indonesia harus menghadapi tantangan deforestasi.
Melansir dari Mongabay, pada tahun 2019, perusahaan tambang nikel PT Weda Bay telah menghilangkan hutan tropis seluas 7.000 hektar di Halmahera Utara sejak memulai proyek penambangan mereka pada tahun 2015. Deforestasi ini telah memengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup spesies-spesies yang tinggal di dalam hutan seperti burung, primata, dan kadal.
Saat ini telah terdapat puluhan perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Tengah. Ada empat kecamatan di wilayah tersebut dimana hutan mulai dibabat untuk aktivitas tambang nikel dan pembangunan smelter, yaitu Maba, Maba Tengah, Buli, dan Weda. Ada 66 izin usaha pertambangan yang mencakup 143.000 hektar wilayah, termasuk di kawasan hutan yang dilindungi.
Banjir
 |
| Banjir di Halmahera Tengah akibat luapan sungai. (Sumber: AMAN Maluku Utara) |
Dampak dari deforestasi masif ini sudah dirasakan oleh warga. Desa-desa di Weda Tengah selalu mengalami banjir sejak 2010. Menurut warga, banjir terparah adalah pada September 2021. Saat itu, air dari sungai besar sekitar Dusun Akelamo, Desa Lelilef Waybulen, dan Desa Lelilef Sawai, meluap ke jalan dan nyaris menenggelamkan rumah-rumah warga.
Daerah-daerah ini kerap menjadi banjir sejak hutan tergerus dalam skala besar, terutama untuk aktivitas pertambangan dan industri. Akibatnya, sejak tahun 2020, banjir selalu terjadi akibat luapan sungai-sungai besar seperti Sungai Kobe, Sungai Ake Sake, dan Ake Wosia.
Padahal dulu, katanya, banjir biasa terjadi 10 tahun sekali. Setelah hutan tergerus akibat aktivitas sejumlah perusahaan tambang, perkampungan mereka mengalami banjir setiap tahun, tidak jauh berbeda dengan Jakarta.
Pencemaran Air
 |
| Aruku Ma Ngairi, Kali yang biasa digunakan di Kawasan Tofubleweng. (Sumber: AMAN) |
Tambang nikel dapat mencemari air tanah dan permukaan dengan limbah tambang yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, arsenik, dan asam sulfat. Pencemaran air dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan yang mengonsumsi dan terpapar air tersebut.
Selain IWIP, perusahaan tambang nikel lain seperti Tekindo juga mengeksploitasi di hulu sungai. Sungai-sungai yang jadi sumber kehidupan masyarakat di sejumlah desa seperti Desa Lelilef Sawai, Desa Lelilef Waibulen, dan Gemaf tidak bisa lagi dikonsumsi karena tercemar, baik karena lumpur maupun aktivitas pertambangan.
Peran Masyarakat Adat Tobelo dalam Menjaga Hutan
1. Menerapkan keberlanjutan hutan dengan tradisi lama
(Sustainability).
Masyarakat Adat Tobelo sejak dulu tidak pernah menjual panennya. Mereka
beranggapan bahwa, jika panen mereka dijual dan ditukar uang, panen akan
cepat habis dan mereka harus bertransaksi dengan uang lagi. Mereka lebih
memilih menyimpan dan mendistribusi hasil panen dengan adil dan
merata.
Dengan tradisi ini, Masyarakat Adat Tobelo selalu menjaga hutan sebagai
sumber penghidupan. Kualitas alam adalah prioritas utama mereka. Berbeda
dengan masyarakat modern yang memprioritaskan uang sehingga mengabaikan
alam. Berkat Masyarakat Adat Tobelo, hutan Halmahera selalu terjaga
keberlanjutannya.
2. Melakukan pengawasan terhadap hutan
Masyarakat Adat Tobelo secara teratur melakukan pengawasan terhadap hutan
di wilayah mereka untuk mencegah tindakan illegal logging dan pembalakan
liar yang merusak hutan.
Aksi mereka tersebut tidak hanya bermanfaat untuk komunitas mereka sendiri,
tetapi juga masyarakat lain yang merasakan manfaat hutan. Lagian, illegal
logging dan pembalakan liar merupakan sumber emisi karbon yang
membahayakan.
3. Memperlakukan sumber air dengan penuh rasa syukur
Konon dahulu kala, seorang perempuan jatuh tenggelam di Kali Molulu saat
dirinya sedang membawa beras panen. Sejak saat itu, padi tumbuh subur dari
dalam kali tersebut. Masyarakat memiliki ikatan spiritualitas yang erat dengan Kali Molulu dan
menjaganya sepenuh hati, sebagai wujud rasa syukur atas panen yang
berlimpah.
Tradisi tersebut bertahan hingga sekarang. Kali Molulu selalu disucikan.
Berkat dijaga oleh mereka selama ratusan tahun, Kali Molulu mampu menjadi
salah satu sumber air utama di Halmahera. Sampai suatu hari perusahaan air
minum kemasan beroperasi di sana dan menurunkan kualitas air
bagi Masyarakat Adat Tobelo. Kemurnian air Kali Molulu kini hanya
dinikmati oleh segelintir orang yang membeli produk dari perusahaan
tersebut, sementara Masyarakat Adat Tobelo tidak bisa lagi menikmati
manfaatnya seperti dulu.
4. Menggunakan sistem rotasi ladang
Masyarakat Adat Tobelo menggunakan sistem rotasi ladang yang memungkinkan
hutan untuk pulih dari penebangan dan menumbuhkan kembali vegetasi sebelum
digunakan kembali.
Sistem rotasi ladang Masyarakat Adat Tobelo adalah praktik pertanian
tradisional di mana tanah digunakan secara bergantian untuk pertanian dan
kemudian dibiarkan pulih untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum
digunakan kembali. Hal ini dilakukan untuk menghindari degradasi tanah dan
menjaga kesuburan tanah.
Menjadi 'Sekutu' bagi Masyarakat Adat
 |
| (Sumber: AMAN) |
Segala tindak tanduk Masyarakat Adat selama ratusan tahun untuk menjaga kelestarian alam, dibalas oleh masyarakat modern dengan konflik berkepanjangan. Sebenarnya kita berhutang budi kepada mereka. Alih-alih mengintimidasi dan mendiskriminasi, seharusnya kita berkolaborasi bersama ciptakan harmoni.
Bayangkan kolaborasi apik yang dapat tercipta antara Masyarakat Adat dan Modern:
Masyarakat kota kembangkan cara modern untuk mengadakan pupuk dan obat-obatan. Kemudian, ibu-ibu dari Masyarakat Adat dikerahkan untuk mengumpulkan semak kirinyuh dan sampah-sampah organik. Masyarakat Adat diberikan mesin-mesin pengolah kompos sederhana dengan tenaga kayuh. Kemudian bergotong-royong membangun gubuk yang menyimpan ratusan kilo kompos dan pupuk cair setiap bulannya.
Masyarakat modern memberikan edukasi terkait tanaman apa saja yang harus ditanam untuk menangkal hama, dan ditanam disekeliling ladang. Sehingga pertanian Masyarakat Adat bisa berkembang lebih pesat.
Masyarakat modern juga bisa turut memberikan edukasi tentang tanaman pangan apa yang kaya akan nutrisi dan tak kenal musim, agar selalu tersedia sepanjang tahun. Dengan begini, krisis pangan bisa turut teratasi.
Alih-alih mengotori sungai tanpa solusi, masyarakat modern bisa memberikan edukasi tentang perancangan penampungan air hujan, misalnya dengan disambungkan ke reservoir. Di penampungan itu, ajari mereka untuk menyaring air misalnya menggunakan biji kelor, kerikil, dan ijuk, sehingga tiap tetes air yang dihasilkan bisa layak minum.
Nah kemudian, karena masyarakat modern 'lebih dekat' dengan sumber informasi ter-update, mereka bisa menginformasikan kepada Masyarakat Adat mengenai perkembangan tanaman obat terbaru dan menginstruksikan Masyarakat Adat untuk mengembangbiakannya. Hasil panennya bisa disalurkan ke produsen obat-obatan herbal atau untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini bisa jadi tambahan pendapatan bagi kedua belah pihak.
Contoh narasi di atas adalah kolaborasi masyarakat modern dan Masyarakat Adat yang memungkinkan. Kita bisa lebih kreatif lagi menciptakan skema kolaborasi yang apik. Apalagi sekarang kemajuan teknologi sudah sangat pesat, kita bisa memanfaatkannya untuk menggali informasi dan edukasi. Selain itu, jadikan sosial media dan media internet lainnya sebagai amplifier raksasa dan strategis untuk menyalurkan suara Masyarakat Adat ke seluruh negeri.







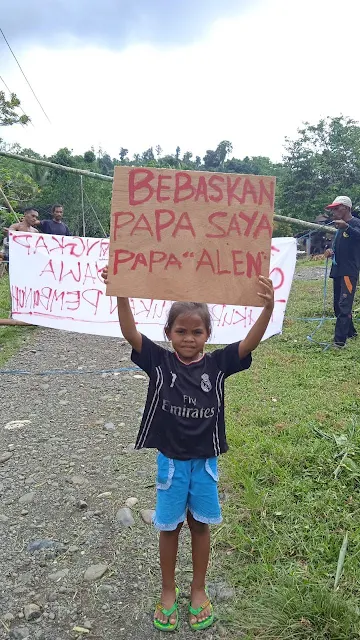






.png)
Komentar